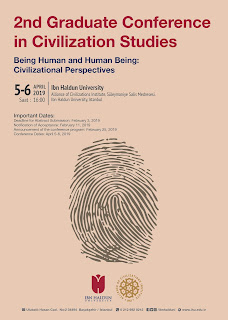Orientalisme yang terbit tahun 1978, mendapatkan perhatian yang terus
berkelanjutan dalam beberapa dekade terakhir. Debat-debat soal Orientalisme, Imperialisme,
dan Euro-centrisme di wilayah-wilayah Muslim di Asia Tenggara telah dimulai
lebih kurang 30 tahun terakhir. Tidak hanya oleh cendekiawan-cendekian Barat
tetapi juga oleh cendekiawan pribumi. Terdapat
Syed Hussein al Attas, Syed Naquib al Attas, Syed Farid al Attas, Jose Rizal,
Armijn Pane, Soedjatmoeko, dan banyak lagi pribumi-pribumi yang mulai membuka
debat soal Kolonialisme, Imperialisme, Eurosentrisme dan native-centrik di
kawasan-kawasan Asia Tenggara.
hingga kemudian membaca pikirannya Elsbeth Lochter Scholten, Dutch Expansion in the Indonesian
Archipelago Around 1900 and the Imperialism Debate, yang terbit pada bulan
Maret 1994 di Jurnal Kajian-Kajian Asia Tenggara. Dalam tulisan ini ia
memaparkan secara mendalam Imperialisme Belanda di Indonesia seperti di Aceh,
Bone, Irian Jaya, Jambi, dan Palembang yang dilakukan atas tujuan memperadabkan
masyarakat pribumi, sebuah tujuan yang kemudian mendapatkan terminologinya
sendiri, eurosentrisme.
Indonesia ini dikenal dengan Kebijakan Etik. Di Malaysia dan negara jajahan
Inggris, dinamai “the Burden of white Man”,
atau “the Debt of Honour”. Tidak
hanya Hindi Timur Belanda tapi di juga Inggris menjual konotasi ini demi
melancarkan exploitasi sumber alam dan sumber daya manusia pribumi. Oleh karena
itu, jumlah manusia manusia kuli paksa semakin bertambah tidak hanya dari dalam
negeri tetapi juga luar negeri seperti kaum Cina dan India. Scholten lebih jauh
beranggapan bahwa Kebijakan Etik ini dipolitisasi oleh pemerintah pusat di The Hague dinilai
dari keuntungan politik yang mengikuti pembahasan trending ini. Ia juga
menyetujui bahwa progrom ‘Kebijakan Etik’ ini juga di pakai untuk meluaskan
expansi militer Belanda di Indonesia, terutama dikawasan-kawasan yang masih
‘bertengkar’ dengan Belanda, seperti di Lombok tahun 1894. Scholten
memperkirakan percaya diri militer Belanda meningkat setelah keberhasilan di
Aceh yang melihat penyerahan diri Sultan terakhir terjadi tahun 1903, tepatnya
1.5 tahun setelah Kebijakan Etik ini diproklamirkan.
Berangkat dari ketertarikan, pada tanggal 6
April lalu, sebuah permulaan kajian, saya bentangkan dalam sebuah konferensi yang
dibuat oleh universitas Ibnu Haldun bekerjasama dengan Medith di Suleymaniye Istanbul bertema “Being Human and Human Being: Perspective on
Civilization” dengan mengangkat Judul “Civilizing
the Uncivilized: Dutch Eurocentrisme in Aceh 1873-1942”. Dalam bentangan selama 15 menit ini, saya
tidak mencoba untuk menolak pencapaian-pencapaian yang telah dibagi oleh Barat.
Dan saya juga tidak mencoba untuk terlibat secara sentimental dengan realita
kolonialisme Belanda di Aceh melainkan hanya fokus pada proses ketibaan dan
meningkatnya keberpihakan masyarakat Aceh pada Belanda dalam konteks misi
peradaban Belanda pada masyarakat pribumi. Diantara yang dibicarakan adalah seputar
minat ekspansi ekonomi dan politik Belanda yang membapaki peperangan Aceh, Kebijakan
Etik, dan terbentuknya format masyarakat Aceh “beradab”, dan “tidak beradab”.
Dengan mediator Prof Erick Ringmar, saya telah menduga bahwa debat dalam
pemikiran pribumi soal eurosentrisme masih akan terus dikonteskan dan ini
merupakan hal yang positif.